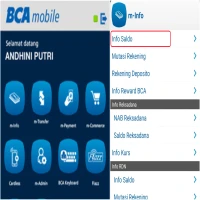Bayang-bayang Ketimpangan Jabar (Bagian I): Kemajuan Tak Sampai ke Desa

Budi Rahman Hakim, Ph.D (Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | Peneliti Transformasi Sosial & Keadilan Wilayah)
Oleh: Budi Rahman Hakim, Ph.D.
Ketika kita bicara tentang Jawa Barat bagian utara hari ini, tiga nama langsung muncul: Karawang, Subang, dan Purwakarta. Ketiganya sering disebut sebagai “sabuk pertumbuhan industri baru”—bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam megaplan Rebana Metropolitan dan perluasan wilayah kereta cepat Jakarta–Bandung. Namun di balik geliat pembangunan, terselip satu ironi: ketimpangan antarwilayah yang makin menganga.
Sejumlah kawasan industri terus dikembangkan. Karawang dikenal sebagai Detroit-nya Asia karena basis otomotifnya. Subang masuk radar global lewat proyek Pelabuhan Patimban dan Kawasan Industri Subang Smartpolitan. Purwakarta sendiri menjadi kawasan transit strategis karena konektivitas jalan tol Cipularang, kereta api, dan kawasan wisata Waduk Jatiluhur. Namun, siapa yang sebenarnya menikmati semua ini? Apakah warga desa, petani lokal, dan pekerja informal ikut mengalami kemajuan?
Infrastruktur Padat
Pembangunan masif jalan, tol, dan bandara di utara telah menciptakan simbol kemajuan yang kontras dengan kondisi desa-desa pinggiran. Di Kecamatan Cibatu, Purwakarta, beberapa jalan desa belum beraspal, dan saat musim hujan menjadi kubangan. Di Karawang bagian selatan, warga mengeluhkan sulitnya akses transportasi ke puskesmas dan sekolah—meski hanya berjarak 15 km dari kawasan industri internasional.
Hal serupa terjadi di Subang barat. Di Desa Cikaum, meski hanya 12 menit dari pintu tol Cikedung, banyak rumah belum teraliri air bersih, dan jaringan listrik PLN sering padam. “Yang berkembang cuma kawasan industri, bukan kampung kami,” keluh Pak Rusli, tokoh masyarakat lokal.Menurut laporan Indeks Pembangunan Wilayah (Bappeda Jabar, 2024), ketimpangan antarwilayah di Jabar utara meningkat 11% dalam lima tahun terakhir. Ketimpangan ini tak hanya mencerminkan masalah teknis, tapi juga soal prioritas politik dan keadilan anggaran.
Program Besar, Warga Kecil
Di atas kertas, program seperti Rebana Metropolitan dirancang untuk mendorong pertumbuhan inklusif. Namun faktanya, akses terhadap pelayanan dasar—air bersih, listrik stabil, transportasi umum, dan sanitasi layak—masih menjadi tantangan di desa-desa Purwakarta, Karawang, dan Subang.
BACA JUGA: Pojokan 259: Mimikri
Laporan Jabar Digital Service tahun 2023 mencatat, lebih dari 27% rumah tangga di Subang dan Purwakarta bagian selatan belum terjangkau air perpipaan. Di Karawang selatan, dari 51 desa yang disurvei, hanya 19 yang memiliki angkutan umum reguler. Bahkan, 36% warga masih menggantungkan diri pada ojek motor pribadi untuk aktivitas ekonomi dan pendidikan harian.
Dalam Development as Freedom, Amartya Sen (1999) menyebutkan bahwa pembangunan sejati harus memperluas kebebasan dan kapabilitas warga. Jika pembangunan hanya dirasakan segelintir korporasi atau kelas menengah urban, maka ia tidak layak disebut kemajuan, tetapi ketimpangan yang disulap dalam narasi investasi.
Menariknya, banyak kampung yang secara administratif berada di tengah-tengah kawasan industri justru menjadi kantong kemiskinan baru. Di Karawang—yang APBD-nya kini menembus Rp 6,3 triliun—masih ada 8 desa berstatus desa tertinggal menurut data DPMD Jabar (Mei 2025). Di Purwakarta, kawasan seputar Bungursari dan Sukatani menjadi lokasi migrasi pekerja informal yang sulit mendapatkan akses KIS, KIP, bahkan identitas kependudukan.
Fenomena ini bukan sekadar “tertangkap” dalam angka statistik. Ia bisa dilihat langsung: barak-barak pekerja harian lepas, kontrakan sempit dengan lima kepala keluarga dalam satu unit, hingga jalan-jalan sempit yang tak pernah tersentuh proyek betonisasi. Ini membuktikan bahwa kemajuan yang dibangun secara spasial tidak selalu linier dengan kesejahteraan sosial.
Terjebak “Efek Pusat”
Salah satu faktor mengapa ketimpangan ini terus berlangsung adalah karena pemerintah daerah—terutama di level kabupaten—terjebak dalam logika proyek pusat. Ketika PSN digulirkan, daerah kerap hanya menjadi pelaksana teknis, bukan perancang kebijakan berbasis kebutuhan lokal. Akibatnya, alokasi APBD sering tidak menyentuh kebutuhan dasar warga desa. Sebaliknya, anggaran habis untuk mendukung program pendukung PSN: jalan penghubung ke kawasan industri, pembangunan rest area, dan infrastruktur kawasan logistik.
Dalam The Right to the City (Lefebvre, 1968), dijelaskan bahwa pembangunan harus dikembalikan kepada warga—mereka yang tinggal, bekerja, dan hidup dalam ruang itu. Jika kota atau kabupaten hanya menjadi etalase investasi, maka hak warga atas kotanya sendiri sedang tergerus diam-diam.
Apa yang Perlu Dilakukan?