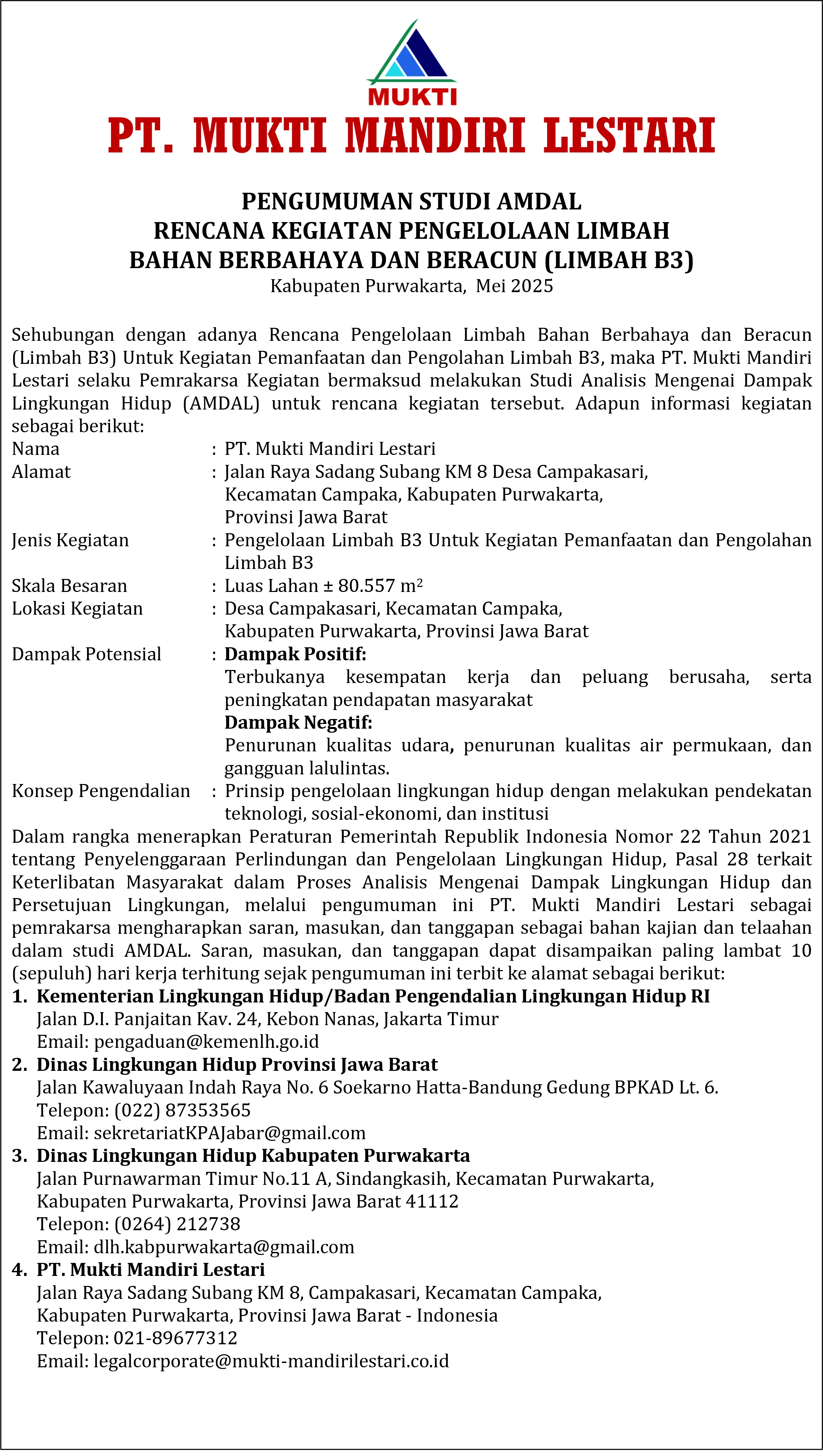Mengenal Musim Kemarau Basah yang Melanda Indonesia Saat Ini

Oleh : Yulia Enshanty, M.Pd
(Guru Geografi SMA di Kabupaten Sukabumi)
Saat ini, Indonesia sedang mengalami fenomena cuaca yang dikenal sebagai musim kemarau basah. Fenomena ini terjadi ketika wilayah Indonesia secara kalender klimatologis telah memasuki musim kemarau, namun curah hujan masih tergolong tinggi di berbagai wilayah. Hal ini menjadi perhatian karena menyimpang dari pola umum musim kemarau yang identik dengan cuaca panas, kering, dan minim hujan. Kemarau basah adalah kondisi anomali cuaca di mana hujan masih terjadi secara signifikan meskipun periode tersebut termasuk dalam musim kemarau. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dalam kondisi normal, musim kemarau di Indonesia biasanya berlangsung pada bulan April hingga Oktober dan ditandai dengan curah hujan di bawah 100 mm per bulan (BMKG, 2023). Namun pada musim kemarau basah, angka ini bisa melampaui batas tersebut. Pada musim kemarau basah, kelembapan udara tetap tinggi, suhu udara tidak terlalu ekstrem, dan pembentukan awan konvektif masih aktif. Fenomena ini dapat dikaitkan dengan beberapa faktor meteorologis dan klimatologis yang memengaruhi dinamika atmosfer di wilayah tropis seperti Indonesia.
Fenomena kemarau basah di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor meteorologis dan klimatologis yang saling berinteraksi. Salah satu penyebab utamanya adalah keterlambatan atau lemahnya hembusan angin Monsun Australia, yang seharusnya membawa udara kering dari selatan menuju utara. Ketika angin ini tidak cukup kuat, wilayah Indonesia bagian selatan tetap menerima pasokan udara lembap, sehingga hujan masih bisa terjadi meskipun seharusnya sudah memasuki musim kemarau. Selain itu, keberadaan siklon tropis di sekitar perairan Indonesia, seperti di Samudra Hindia atau Laut Filipina, juga berkontribusi dalam menarik massa udara lembap dari lautan ke daratan. Mekanisme ini memperkuat potensi terbentuknya awan konvektif yang menghasilkan hujan. Faktor lainnya adalah aktivitas gelombang atmosfer seperti Madden-Julian Oscillation (MJO), gelombang Kelvin, dan Rossby yang bergerak di sekitar wilayah tropis dan dapat memicu peningkatan konveksi atau pembentukan awan hujan. Ketika fase basah MJO melintasi Indonesia, curah hujan cenderung meningkat walaupun musim kemarau sedang berlangsung. Tidak kalah penting, faktor lokal seperti suhu permukaan laut yang tetap hangat, kontur wilayah, serta pertemuan angin lokal juga turut memperbesar peluang terjadinya hujan. Kombinasi dari berbagai dinamika atmosfer ini menciptakan kondisi anomali yang membuat musim kemarau tetap diwarnai hujan, atau dikenal sebagai kemarau basah.
BACA JUGA: Bersama STEM/STEAM, Matematika Menjadi Wahana Kreativitas dan Solusi Nyata
Musim kemarau basah membawa berbagai dampak signifikan yang perlu mendapat perhatian serius, terutama di sektor pertanian, infrastruktur, dan kesehatan masyarakat. Di bidang pertanian, perubahan pola curah hujan yang tidak menentu dapat mengganggu sistem tanam yang sudah dirancang berdasarkan kalender musim normal. Ketidakpastian cuaca ini menyulitkan petani dalam menentukan waktu tanam, pemupukan, dan panen, yang pada akhirnya berpotensi menurunkan produktivitas dan meningkatkan risiko gagal panen. Selain itu, kelembapan tinggi juga menjadi kondisi yang ideal bagi perkembangan hama dan penyakit tanaman. Di sisi lain, hujan yang masih turun di musim kemarau dapat menyebabkan banjir lokal, khususnya di daerah perkotaan yang memiliki sistem drainase kurang memadai. Genangan air yang terjadi secara tiba-tiba bisa mengganggu aktivitas masyarakat dan merusak fasilitas umum. Dampak lain yang tak kalah penting adalah terhadap kesehatan masyarakat, di mana kelembapan tinggi dan cuaca yang berubah-ubah dapat memicu peningkatan kasus penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), demam berdarah, dan penyakit kulit. Oleh karena itu, pemahaman terhadap dampak-dampak ini sangat penting agar masyarakat dapat mengambil langkah preventif yang sesuai.
Dalam menghadapi musim kemarau basah, masyarakat diimbau untuk lebih waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat terjadi sewaktu-waktu. BMKG menyarankan agar masyarakat secara aktif mengikuti informasi cuaca melalui kanal resmi seperti situs web, aplikasi mobile, dan media sosial BMKG untuk mendapatkan pembaruan cuaca harian serta peringatan dini. Kesadaran terhadap kondisi cuaca sangat penting, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir atau longsor. Di sektor pertanian, para petani dianjurkan untuk menyesuaikan jadwal tanam dan pola budidaya mereka berdasarkan kondisi cuaca aktual, serta menjalin komunikasi intensif dengan penyuluh pertanian guna meminimalkan risiko gagal panen. Selain itu, pemerintah daerah dan masyarakat diharapkan melakukan upaya mitigasi seperti pembersihan saluran drainase, pengerukan sungai kecil, dan penguatan sistem resapan air untuk mencegah genangan dan banjir lokal. Di lingkungan sekolah maupun komunitas, edukasi mengenai perubahan pola cuaca dan kesiapsiagaan bencana juga perlu ditingkatkan. Dengan upaya kolektif dan koordinasi yang baik antara masyarakat, pemerintah, dan instansi terkait, dampak negatif dari musim kemarau basah dapat diminimalkan, serta ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim dapat semakin diperkuat.
Musim kemarau basah yang melanda Indonesia saat ini merupakan fenomena iklim yang kompleks dan erat kaitannya dengan dinamika atmosfer global. Memahami karakteristik, penyebab, dan dampaknya menjadi penting agar masyarakat dapat mengambil langkah adaptif dan mitigatif yang tepat. Dalam konteks perubahan iklim global yang semakin terasa, peristiwa seperti kemarau basah kemungkinan akan menjadi lebih sering terjadi di masa depan, sehingga pemahaman dan kesiapsiagaan menjadi kunci penting. Dengan memahami penyebab, dampak, serta langkah-langkah mitigasi yang dapat dilakukan, diharapkan masyarakat semakin tanggap dan adaptif terhadap dinamika iklim yang semakin kompleks. Musim kemarau basah bukan sekadar anomali cuaca biasa, melainkan cerminan dari perubahan iklim global yang nyata dan terus berkembang. Oleh karena itu, kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait sangat penting untuk membangun ketahanan lingkungan dan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kondisi cuaca ekstrem di masa mendatang.(*)
BACA JUGA: Leuit, Simbol Ketahanan Pangan dan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Kasepuhan Gelar Alam