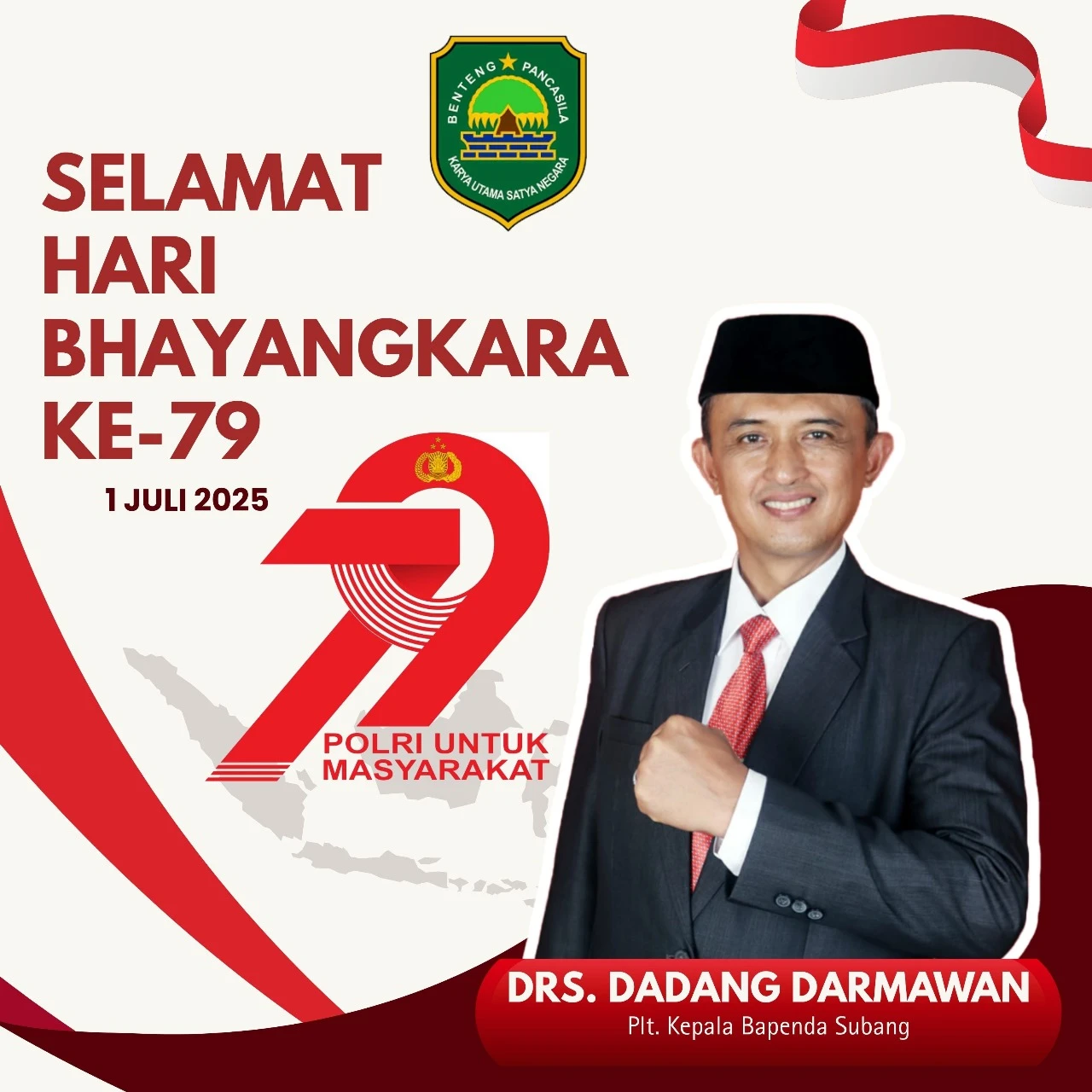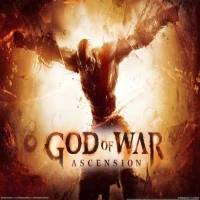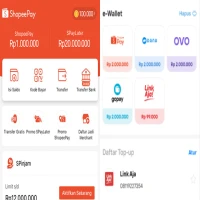Mengelola Sumber Daya Alam untuk Masa Depan Berkelanjutan: Nature-Based vs Human-Based ?

Dalam situasi krisis ekologis global saat ini, keberanian untuk bertransformasi tidak bisa ditunda. Sudah saatnya kita tidak hanya membicarakan pendekatan mana yang lebih unggul, tetapi bagaimana membangun ekosistem pengelolaan yang sehat, demokratis, dan adil. Alam bukanlah objek yang harus ditaklukkan, melainkan mitra yang harus dihormati. Manusia bukanlah penguasa tunggal bumi, tetapi bagian dari jaring kehidupan yang saling bergantung. Pengelolaan sumber daya alam bukan hanya soal pembangunan, tetapi juga soal keberadaban.
Sayangnya, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam di Indonesia masih berat sebelah dan cenderung berpihak pada pendekatan berbasis manusia yang berdampak pada eksploitasi SDA yang mengatasnamakan “kesejahteraan dan ekonomi”. Di Indonesia, sebetulnya tantangan dalam pengelolaan SDA tidak hanya bersumber dari pilihan pendekatan, tetapi juga dari aspek tata kelola (governance) yang belum sehat. Masih sering kita lihat di berita-berita terkait praktik korupsi dalam sektor pengelolaan sumber daya alam, tumpang tindih perizinan, lemahnya penegakan hukum lingkungan, hingga rendahnya transparansi dalam pengelolaan sumber daya di daerah menjadi hambatan sistemik. Data ASEAN Environmental Democracy Observatory tahun 2024 terkait Environmental Democracy Index (EDI) menunjukkan bahwa Indonesia masih tertinggal dalam hal akses informasi dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan lingkungan. Meskipun telah hadirnya kebijakan seperti UU Keterbukaan Informasi Publik 2008 dan UU Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup 2009, implementasi nyata masih lemah; termasuk sistem PROPER yang belum memberikan akses publik luas dan partisipasi yang bermakna. Akibatnya, masyarakat—terutama di daerah terdampak—sering cuma tahu soal rencana tambang, reklamasi atau proyek besar setelah dimulai, bukan saat perencanaan. Ini menunjukkan bahwa perbaikan pengelolaan SDA bukan hanya persoalan teknis atau ekologis, melainkan juga reformasi kelembagaan dan tata kelola demokratis yang berpihak pada rakyat dan lingkungan.
Masih banyak kasus-kasus lainnya seperti kawasan hutan yang dikonversi menjadi penggunaan lahan lainnya seperti perkebunan, buruknya pengeloaan hutan Taman Nasional Tesso Nilo, praktek tambang nikel di RajaAmpat, dan sebagainya. Ada juga, reklamasi pantai yang mengorbankan wilayah nelayan tradisional yang menjadi contoh nyata dominasi pendekatan ekstraktif. Sepertinya, paradigma “ekonomi di atas segalanya” masih menjadi penggerak utama kebijakan saat ini, sementara prinsip keberlanjutan dan keadilan ekologis sering kali sekadar menjadi jargon. Meski demikian, terdapat sejumlah inisiatif positif yang menunjukkan potensi pendekatan berbasis alam, seperti restorasi ekosistem gambut, pengembangan ekowisata berbasis masyarakat di wilayah adat, atau program Kampung Iklim yang memberikan insentif pada upaya pelestarian lingkungan berbasis komunitas. Tantangannya adalah bagaimana menjadikan pendekatan-pendekatan ini sebagai arus utama kebijakan, bukan sekadar proyek percontohan.
Melihat realitas tersebut, sudah saatnya kita mendorong transformasi paradigma dalam pengelolaan sumber daya alam. Pendekatan yang semata-mata mengandalkan manusia dan teknologi tidak akan cukup menghadapi kompleksitas krisis lingkungan saat ini. Di sisi lain, pendekatan berbasis alam perlu didukung dengan kapasitas kelembagaan, teknologi, dan partisipasi publik yang kuat. Dalam konteks ini, masyarakat memiliki peran penting, tidak hanya sebagai penerima dampak, tetapi juga sebagai pengambil keputusan. Konsumsi sadar lingkungan, partisipasi dalam pengawasan kebijakan lingkungan, serta pendidikan ekologis kepada generasi muda menjadi bagian dari strategi kolektif untuk mewujudkan pengelolaan SDA yang adil dan berkelanjutan.
Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya alam bukanlah semata-mata persoalan teknis atau ilmiah, melainkan refleksi dari nilai, pilihan moral, dan keberpihakan kita terhadap masa depan. Kita membutuhkan kebijakan yang tidak hanya efisien, tetapi juga etis dan ekologis. Mengelola sumber daya alam dengan bijak berarti memahami bahwa kita bukanlah pemilik tunggal alam, melainkan bagian dari jejaring kehidupan yang saling bergantung. Semoga dengan pendekatan yang tepat dan kesadaran kolektif, Indonesia dapat menjadi pelopor pengelolaan sumber daya alam yang mengintegrasikan kekuatan alam dan kearifan manusia demi masa depan yang lestari.(*)